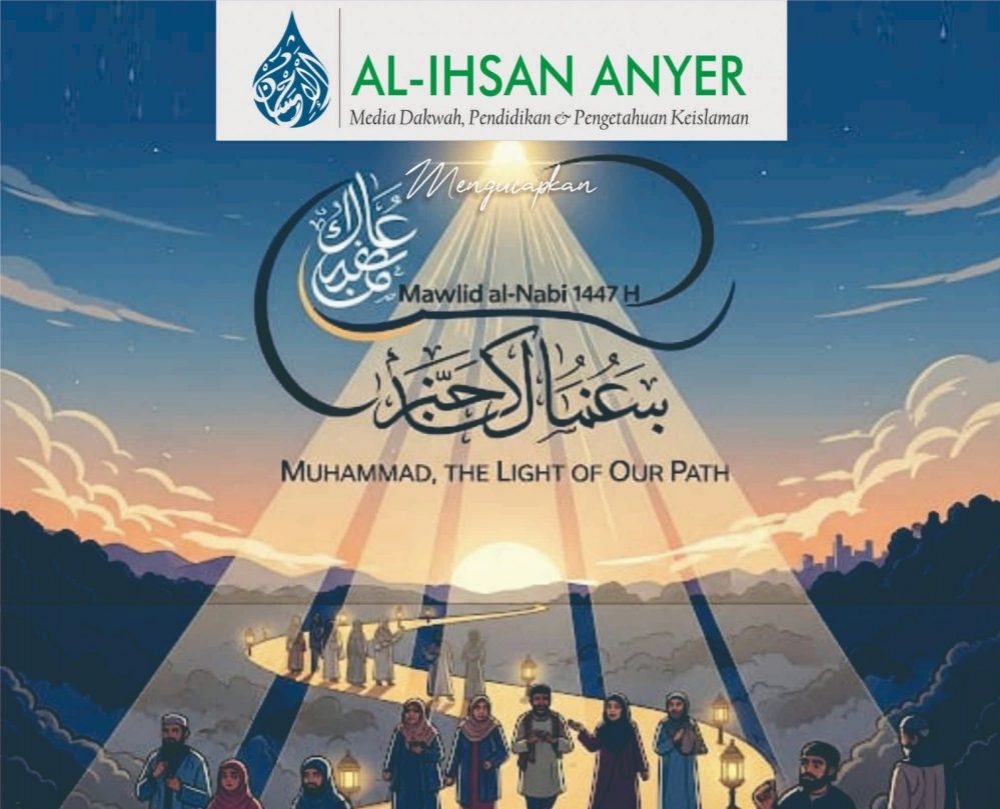Sudah menjadi hukum kepastian Tuhan, sunnatullah, bahwa manusia dan kehidupan mereka amat beragam. Begitu pula dengan bangsa Indonesia yang memiliki aneka ragam suku, budaya, adat-istiadat, dan agama. Oleh karena itu pula, masyarakat Indonesia sering dinyatakan bersifat majemuk, plural, serta multikultural. Dalam masyarakat yang memiliki heterogenitas yang tinggi seperti ini, tidak jarang muncul konflik dan bahkan konflik terbuka di masyarakat, baik etnis atau kerusuhan rasial maupun konflik yang berbasis agama. Kasus-kasus kerusuhan yang terjadi di Kalimantan Barat dan Tengah, Sulawesi Barat, Maluku/Ambon, atau Papua, menunjukkan bahwa konflik SARA bisa meledak kapan pun dan di mana pun di bumi Nusantara ini.
Dalam sebuah masyarakat yang majemuk seperti Indonesia, akan selalu selalu muncul prasangka yang memengaruhi interaksi sosial antara berbagai golongan. Misalnya, setiap golongan penduduk di masyarakat Indonesia menyandang perangkat prasangka dari warisan generasi sebelumnya. Golongan pribumi, misalnya, hidup dengan sejumlah prasangka terhadap keturunan Cina, dan sebaliknya. Golongan penduduk Islam menyimpan sejumlah prasangka terhadap golongan Kristen, dan sebaliknya.
Benar, prasangka sosial dalam masyarakat majemuk tidak bersifat langgeng. Dari waktu ke waktu, berbagai prasangka itu berubah. Perubahan dalam prasangka ini dapat menuju interaksi sosial yang lebih baik atau lebih jelek. Dalam kurun waktu tertentu, golongan-golongan penduduk bisa menjadi lebih saling mencurigai, saling membenci, tetapi juga bisa menjadi saling memahami dan saling menghormati. Ini ditentukan oleh cara berbagai golongan penduduk dalam suatu masyarakat majemuk mengelola prasangka-prasangka sosial yang ada dalam diri masing-masing. Kegagalan dalam mengelola prasangka-prasangka sosial itu akan berakibat fatal, sebagaimana telah dicontohkan di atas.
Konflik-konflik berdarah yang acapkali menelan korban jiwa itu, sebenarnya tidak perlu terjadi jika masyarakat Indonesia mengedepankan nilai-nilai saling menghargai, menghormati serta mau menerima satu sama lain, atau bahkan saling bekerja sama. Inilah dasar-dasar toleransi zaman sekarang, yang tidak hanya mencakup sikap dan tingkah laku hidup damai secara berdampingan, tetapi juga membangun kerja sama.
Sikap toleran terhadap aneka perbedaan, menerima dan menghormati keberagaman, serta kesediaan untuk bekerja sama dengan liyan, memang bukan sesuatu yang bisa dibangun dalam sehari. Tetapi memerlukan proses yang panjang, dan melibatkan banyak pihak. Mulai dari lingkungan keluarga, peran serta masyarakat, negara, sampai institusi-institusi sosial seperti lembaga-lembaga pendidikan. Termasuk sekolah.
Sekolah, kita pahami, bukan sekadar wahana untuk mentransfer ilmu pengetahuan dan keterampilan kepada peserta didik, melainkan juga berfungsi untuk menanamkan dan mengembangkan nilai-nilai dasar kemanusiaan, yang menjadi acuan hidup bersama. Dan toleransi adalah salah satu nilai yang perlu ditumbuhkan di berbagai jenjang persekolahan. Nilai ini tidak cukup diajarkan secara verbal, tetapi harus diikuti dengan penanaman sikap dan perilaku keseharian, baik di dalam maupun di luar lingkungan sekolah. Kunjungan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ke sebuah seminari di Malang dengan membawa serta putranya yang masih anak-anak, merupakan salah satu conoh konkret dalam menanamkan nilai dan budaya toleransi, khususnya toleransi antar-umat beragama. . .
Penghargaan atas Kemajemukan
Sikap dan perilaku toleran hanya bisa tumbuh di atas kesadaran terhadap keberagaman etnis dan budaya. Yakni sikap menghormati terhadap berbagai perbedaan yang merupakan ciri utama sebuah masyarakat majemuk. Penghargaan atas keberagaman etnis dan budaya juga berarti memperlakukan keanekaragaman budaya dan etnis dalam kesederajatan. Konsep ini lebih dikenal dengan sebutan multikulturalisme. Multikulturalisme meliputi pemahaman, penghargaan dan penilaian atas budaya seseorang dan sebuah penghormatan dan keingintahuan tentang budaya etnis orang lain. Ia juga mencakup penilaian terhadap budaya-budaya orang lain, bukan dalam arti menyetujui seluruh aspek dari kebudayaan tersebut, melainkan mencoba melihat bagaimana kebudayaan tertentu dapat mengekspresikan nilai bagi anggota-anggotanya sendiri.
Dalam kebudayaan multikultural setiap individu sejatinya mempunyai kemampuan berinteraksi dan bertransaksi meskipun latar belakang kultur masing-masing berbeda. Hal ini karena pada dasarnya sifat manusia itu akomodatif, asosiatif, suka beradaptasi, fleksibel, dan punya kemauan untuk saling berbagi. Pandangan ini mengisyaratkan, bahwa keberagaman budaya mengandung unsur jamak serta sarat dengan nilai-nilai kearifan. Dalam konteks membangun tatanan sosial yang kokoh, maka nilai-nilai kearifan ini dapat dijadikan sebagai sumbu pengikat dalam berinteraksi dan bersosialisasi antarindividu atau antarkelompok sosial. Hanya dengan mempersempit perselisihan budaya yang tidak kondusif, maka siklus kehidupan sosial masyarakat yang majemuk akan terwujud dalam prinsip-prinsip dasar yang bisa saling menghargai, menghormati dan menjaga satu dengan yang lain. Inilah esensi dari tatanan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai toleransi.
Toleransi, dengan demikian, bisa kita maknai sebagai nilai dan tradisi yang niscaya dalam sebuah masyarakat yang majemuk dan multikultur. Tanpa toleransi, masyarakat akan selalu berada dalam suasana konfliktual yang destruktif, saling bermusuhan, penuh arogansi dan tidak stabil. Toleransilah yang bisa membuat perbedaan menjadi kekuatan, mentransformasikan keragaman menjadi keharmonisan. Toleransi memungkinkan masyarakat plural bergerak maju secara dinamis dalam situasi sosial yang damai dan stabil.
Pendidikan Agama dan Intoleransi
Salah satu problem toleransi di Indonesia adalah intoleransi agama (religous intolerance). Jika tidak tertangani, persoalan ini akan menjadi ancaman serius bagi keberadaan dan keberlangsungan masyarakat kita yang multikultural. Dikatakan demikian, karena hakikatnya intoleransi agama merupakan tindakan pembedaan, pengabaian, larangan atau pengutamaan yang didasarkan pada agama atau kepercayaan dan yang tujuannya atau akibatnya meniadakan atau mengurangi pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan mendasar atas dasar yang setara.
Kasus-kasus intoleransi agama pada umumnya didominasi oleh kekerasan dan penyerangan, penyebaran kebencian, pembatasan berpikir dan berkeyakinan, penyesatan dan pelaporan kelompok yang diduga sesat, pembatasan aktivitas/ritual keagamaan, pemaksaan keyakinan, dan konflik tempat ibadah. Sedangkan bentuk tindakan intoleransi yang paling banyak adalah penyebaran kebencian terhadap kelompok, negara/bangsa tertentu; penyerangan, perusakan, dan penggerebekan rumah, bangunan, atau tempat ibadah; tuntutan pembubaran Ahmadiyah; penyesatan; pelarangan aktivitas/ritual/busana keagamaan; pelarangan dan tuntutan penarikan penyiaran dan penerbitan; fatwa sesat; intimidasi; laporan sesat kepada aparat terkait; tuntutan pembubaran kelompok sesat; penolakan pendirian rumah ibadah; tuntutan penegakan syariat Islam; pengusiran, pemberhentian kerja, pelarangan kegiatan mirip agama lain, dan pemukulan.
Tindakan intoleransi agama itu sejatinya berlawanan dengan nilai-nilai dasar agama. Dalam Islam, misalnya, terdapat beberapa nilai yang bisa menjadi acuan dalam bertoleransi. Pertama, prinsip keberagaman atau pluralitas (ta’addud) merupakan hukum alam (sunnatullah) yang tidak akan berubah dan tidak bisa ditolak. Secara gamblang Al-Qur’an menyatakan bahwa manusia itu diciptakan dalam berbagai bangsa dan suku. Oleh karena itu, keanekaragaman ini harus diterima sebagai kenyataan yang mesti dihargai dan dipandang secara optimistis dan positif sebagai salah satu tanda-tanda kekuasaan Tuhan. Kedua, prinsip persamaan (al-musawah) atau kesetaraan. Menurut ajaran Al-Qur’an dari segi hakikat penciptaan, antara manusia yang satu dan manusia lainnya tidak terdapat perbedaan. Ketiga, prinsip kebebasan yang meliputi kebebasan beragama dan kebebasan berpikir. Kebebasan beragama adalah kebebasan paling fundamental dalam urusan sosio-politik kehidupan manusia. Keempat, prinsip keadilan (al-‘adalah). Dalam Islam, salah satu semangat dasar yang dibawa oleh Al-Qur’an adalah keadilan bagi semua umat manusia.
Akan tetapi, jika kita menelusuri buku-buku ajar agama yang diajarkan di sekolah dasar sampai sekolah menengah, katakanlah buku Pendidikan Agama Islam, isinya lebih fokus pada ajaran atau doktrin keimanan dan tata pelaksanaan ibadah. Ajaran mengenai iman pun lebih menekankan kepada penguatan akidah, dan hampir tidak menyentuh dimensi-dimensi yang lebih luas dari konsekuensi keberimanan. Begitu pula dengan ritual-ritual ibadah yang dibahas secara lebih eksklusif dan ritualistik. Tidak atau kurang memberikan ruang kepada dimensi-dimensi sosial atau moral yang terkandung dalam sebuah peribadatan. Dimensi sosial dan moral itu termasuk di dalamnya adalah nilai dan tradisi toleransi.
Toleransi atau tasamuh sejatinya hanya satu dari sekian syarat yang mesti dipenuhi dalam mewujudkan moderatisme beragama dalam kehidupan sehari.