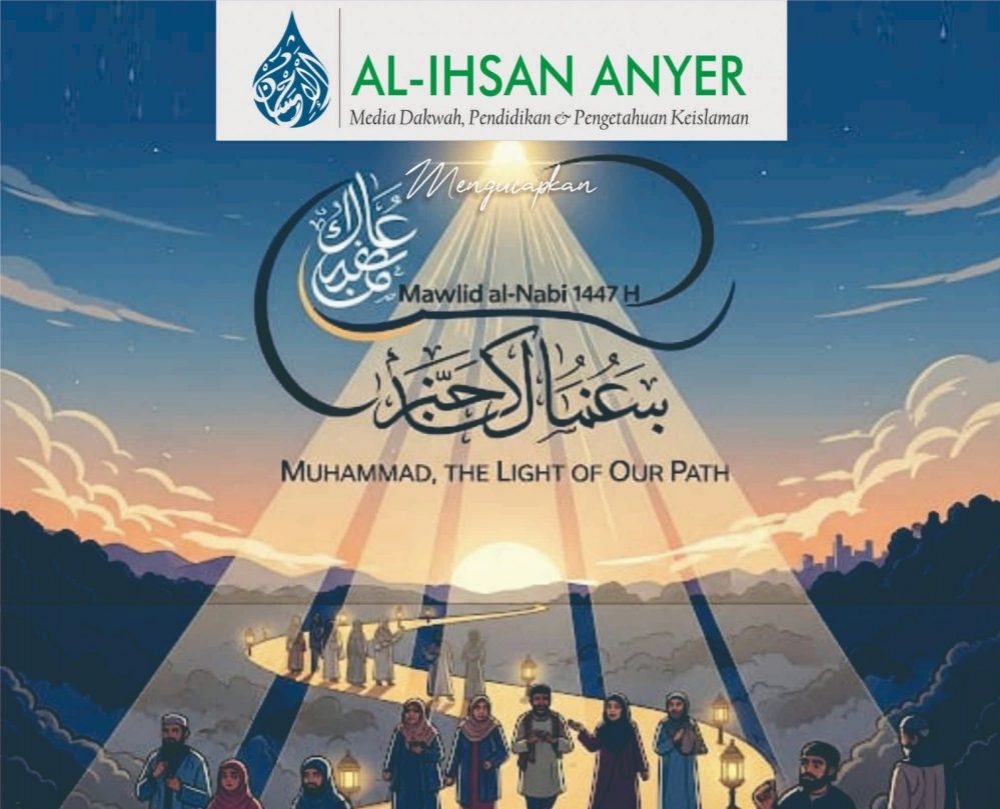Malam merupakan saat-saat yang indah untuk beribadah. Namun tak berarti orang harus menjadi loyo karena menghidupkan malam.
“Anakku, kamu jangan lebih lemah dari seekor ayam jantan. Ia bisa berkokok menjelang subuh, sementara kamu masih mendengkur.” Demikian nasihat Lukmanul Hakim kepada putranya, sebagaimana diriwayatkan Al-Hasan Al-Bashri.
Bagi para ahli ibadah, malam merupakan saat-saat yang bagus untuk menyaksikan keagungan dan kemuliaan Allah. Dan Allah pun memberi pujian kepada penggiat qiyamul lail atau sembahyang malam. “Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam; sedangkan pada dini hari memohon ampunan.” (Q.S. 51: 17-18). Menurut Al-Qasimi dalam kitab tafsirnya Mahasinut Ta’wil, hikmah diistimewakannya waktu menjelang subuh tak lain karena waktu itulah kesempatan yang paling senggang bagi manusia untuk mencari ‘embusan’ dzat Maha Pengasih dan kelembutan Dzat Yang Maha Suci. Saat itu, kata mufassir ini, melaksanakan ibadat memang terasa amat berat. Tetapi niat menjadi bersih, keinginan menggelora, ditambah amat dekatnya Allah Yang Maha Tinggi dan Yang Maha Kudus.
Pernah Al-Hasan ditanya seseorang: “Mengapa orang-orang yang melakukan sembahyang malam menjadi orang-orang yang berwujud paling bagus?” Ia pun menjawab, “Karena mereka menyendiri bersama Yang Maha Pengasih, kemudian menurunkan cahaya-Nya kepada mereka.” Ia juga pernah menyatakan, “Saya belum pernah menemukan sesuatu yang lebih berat dalam beribadat melebihi salat tengah malam.”
Tapi boleh jadi, lantaran terus begadang sebagian ahli ibadat menjadi loyo. Ada cerita dari Aisyah r.a. Suatu hari janda Rasulullah SAW ini melihat beberapa pemuda lewat. Langka mereka tampak lamban . “Siapa mereka?” tanya Aisyah kepada kawan-kawannya.
“Ahli ibadat,” mereka menjawab.
“Ah, kalian kan tahu Umar ibn Khattab,” katanya. “Dia itu kalau berjalan, langkahnya cepat . Kalau bicara suaranya lantang. Kalau memukul, keras. Kalau makan, kenyang. Padahal dia sebenar-benar ahli ibadat.”
Adapun Al-Hasan Al-Bashri, yang kita kutip, merupakan generasi tabi’in (pasca Sahabat) yang lahir di Madinah pada 21 H./642 M. Ia putra Abul Hasan, orang asal Masian yang dibawa ke Madinah sebagai tawanan perang. Di sini Abul Hasan dipersaudarakan dengan Zaid ibn Tsabit r.a. dan menikah dengan Khairah dari marga Umm Salamah r.a. dari perkawinan inilah Al-hasan dilahirkan.
Setahun setelah perang Siffin (657 M), yang melibatkan Ali dan Mu’awiyah, Al-hasan dibawa keluarganya ke Wadi Al-Kura, lalu menetap di Basrah, kota kamp militer, sekitar 80 kilometer barat daya Teluk Persia. Selama tiga tahun Al-Hasan muda (670-673 M) terlibat dalam beberapa ekspedisi ke bagian timur Persia (Iran). Dalam waktu singkat, Basrah berkembang lebih dari sekadar pos militer, tapi juga pusat kegiatan keagamaan dan intelektual. Dan Al-Hasan menjadi tokoh sentralnya. Ia pun lebih masyhur dengan sebutan Al-Hasan Al-Bashri alias Al-Hasan orang Basrah. Lebih dari seorang yang terpelajar, meskipun pikiran-pikirannya tidak tersusun sistematis, Al-Hasan dikenal saleh dan asketis (zuhud) dan punya kepribadian.
Kepada khalifah Abdul Malik, Al-Hasan, misalnya, pernah menulis: “Wahai Amirul Mukminin… Tirani dan ketidakadilan bukanlah ajaran Tuhan. Ajaran-Nya adalah perintahnya mengenai keadilan, kebajikan, dan menyantuni kepada yang paling dekat.”
Ketika Al-Hasan mangkat, 1 Rajab 110 H/10 Oktober 728, ia mendapat penghormatan penuh dari seluruh penduduk kota. Dilaporkan, di hari pemakamannya tidak seorang pun sembahyang asar di masjid Basrah. Semua mengiring jenazah.