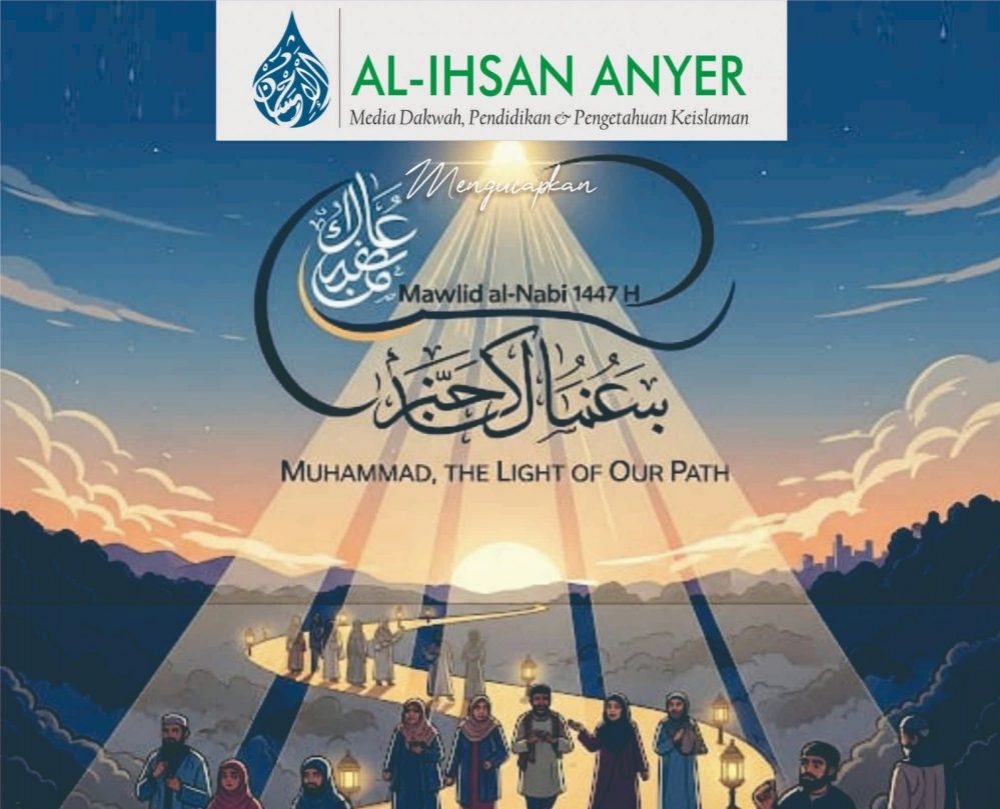Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. [Q.S. Al-Mujadalah: 11].
Tidak syak lagi, kutipan ayat di atas menggambarkan bahwa orang yang berpengetahuan, seperti halnya orang yang beriman, memiliki kedudukan yang teramat tinggi dalam pandangan Allah. Seperti ditegaskan firman Allah yang lain, memang tidak sama antara mereka yang berpengetahuan dan yang tidak. “Katakanlah, ‘Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?’ Sesungguhnya orang-orang yang berakal sajalah yang dapat menerima pelajaran.” [Q.S. Az-Zuma: 9]. Sunnah Nabi sendiri penuh dengan nasihat supaya berpengetahuan dan menjauhi kebodohan. Dengan menggunakan akal pikirannya, manusia dapat mengetahui sesuatu. Hasil dari mengetahui sesuatu itu lazim disebut pengetahuan. Ilmu pengetahuan dan iman merupakan modal bagi seseorang yang akan mengantarnya menuju kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Itulah makna mengapa orang yang beriman dan berpengatahuan memiliki derajat yang tinggi di hadapan Allah SWT.
Anugerah ilmu pengetahuan yang dimiliki manusia tentu tidak datang begitu saja, laksana hujan yang turun dari langit. Manusia diharuskan untuk menuntutnya sejak dari buaian sampai tepi kuburan (minal mahdi ilal lahdi). Keharusan untuk menuntut ilmu sepanjang hayat ini merupakan sebuah tugas suci atau jihad di jalan Allah. Sebuah hadis menyatakan, “Man kharaja fii thalibil ‘ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji’a. Artinya, “Barang siapa keluar untuk mencari ilmu maka dia berada di jalan Allah sampai kembali.” [H.R. Tirmidzi]. Dalam hadis riwayat Bukhari dinyatakan, “Barangsiapa menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu, maka Allah memudahkan baginya ke jalan menuju surga.”
Oleh karena itu, tidak mengherankan pula jika generasi awal Islam atau generasi salaf memiliki semangat atau etos keilmuan yang sangat kuat, sehingga muncullah sarjana-sarjana Muslim dalam berbagai bidang keilmuan yang senantiasa akan dikenang oleh sejarah. Etos keilmuan atau semangat thalabul ilmi ini, meskipun mengalami turun-naik, terus diwariskan dari generasi ke generasi. Bahkan putra Banten sendiri, yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani, tercatat sebagai ulama yang reputasinya diakui di dunia Islam. Beliau bergelar Sayyid ulama’il Hijaz atau penghulu ulama Hijaz yang menulis puluhan kitab itu. Kitab-kitab beliau, seperti Tafsir Al-Munir, sampai sekarang masih menjadi pegangan para kiai lainnya, bukan hanya di Indonesia tetapi juga rujukan ulama di negara-negara Islam lainnya. Kitab-kitab karangan Syekh Nawawi memang masih dipelajari di pesantren-pesantren salafi alias tradisional di Jawa, selain di lembaga-lembaga tradisional di Timur Tengah, dan menjadi bahan kajian di perguruan tinggi Islam. Banyak orang Indonesia-Melayu atau orang Nusantara yang belajar kepada Syekh Nawawi, dan kebanyakan dari mereka kemudian menjadi kiai-kiai terkemuka di pesantren-pesantren di Tanah Air, di antaranya K.H. Kholil dari Bangkalan, Madura, K.H. Hasyim Asy’ari, pendiri Pesantren Tebuireng di Jombang dan pendiri Nahdlatul Ulama, dan K.H. Asnawi dari Caringin, Pandeglang, Banten.
Harus diakui, etos keilmuan di kalangan kaum Muslim dewasa ini boleh dikatakan sedang mengendung. Di zaman yang menjadikan materi sebagai ukuran keberhasilan ini, masyarakat cenderung berpikir dan bersikap pragmatis mengenai pengetahuan. Artinya, hanya jenis-jenis pengetahuan yang bisa menguntungkan secara materil atau menghasilkan uang itulah yang harus dikuasai. Dengan demikian, pengetahuan atau ilmu hanya sekadar alat untuk mencari harta. Posisi yang benar, seharusnya harta adalah sarana atau modal untuk menuntut ilmu. Bukan sebaliknya. Tetapi sekarang, tidak sedikit kita menyaksikan kaum Muslim yang enggan mengorbankan hartanya demi menuntut ilmu. Kalaupun rela, mereka berharap ilmu yang diperoleh itu akan menghasilkan uang banyak.
Jika kita ingin melahirkan ulama-ulama berkaliber dunia seperti Syekh Nawawi, maka tidak ada jalan bagi generasi muda Muslim, khususnya kalangan santri, kecuali memiliki semangat keilmuan yang tinggi. Memang tidak mudah, karena untuk itu seseorang harus siap menghadapi berbagai tantangan dan cobaan sebagaimana lazimnya orang yang ingin berhasil. Termasuk korban harta. Bahkan setelah menjadi alim atau orang berilmu pun, dia harus diuji dengan berbagai cobaan yang bisa merusak integritas keulamaannya.***