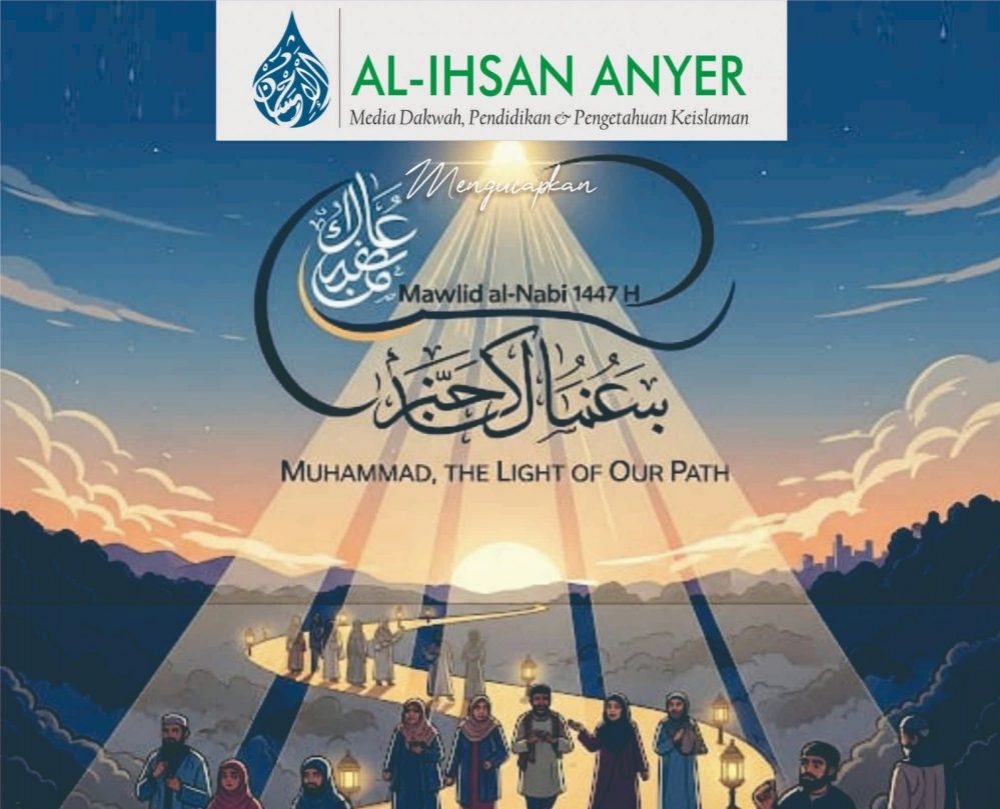H. A. Suryana Sudrajat
Apa yang membedakan manusia dari makhluk lainnya?
Banyak sudah jawaban yang diberikan para ahli pikir atas pertanyaan ini. Satu di antaranya adalah bahwa manusia adalah animal educandus dan animal educandum sekaligus. Sejak keberadaannya dalam kondisi kehidupan yang primitif hingga yang paling tinggi tingkat perkembangannya, manusia adalah satu-satunya makhluk yang bisa dididik dan mampu mendidik (termasuk mendidik dirinya sendiri). Maka tidak berlebihan kalau dinyatakan bahwa pendidikan manusia berlangsung sepanjang hayatnya. Erat kaitannya dengan pandangan ini ialah pendapat yang menyatakan, bahwa pemberdayaan manusia sangat ditentukan oleh pendidikannya. Dengan kata lain, pendidikan merupakan ikhtiar yang tertuju pada pemberdayaan segenap potensi manusia.
Pemberdayaan potensi manusia itu mencakup tiga hal yang paling mendasar. Pertama, ranah afektif yang tercermin pada kualitas keimanan, ketakwaan, akhlak mulia termasuk budi pekerti luhur serta kepribadian unggul, dan kompetensi estetis. Kedua, domain kognitif yang tercermin pada kapasitas pikir dan daya intelektualitas untuk menggali dan mengembangkan serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Ketiga, ranah psikomotorik yang tercermin pada kemampuan mengembangkan keterampilan teknis, kecakapan praktis, dan kompetensi kinestetis. Dalam bahasa Ki Hajar Dewantara disebut rasa, cipta dan karsa. Karena itu pula, pendidikan dipahami sebagai proses sistematis untuk meningkatkan martabat manusia secara holistik, yang memungkinkan ketiga dimensi kemanusiaan paling mendasar tersebut dapat berkembang secara optimal. Jika hal ini tercapai maka akan lahir generasi insan kamil atau manusia paripurna.
Ini sebuah missi profetik, yang bukan main berat. Berat karena amanah itu harus dipikul ketika kita sebagai bangsa masih berhadapan dengan situasi yang carut-marut.. Ini baru faktor internal. Sebab di luar kita sudah harus dihadapkan dengan berbagai tantangan yang tidak kalah keras dan hebatnya. Misalnya, globalisasi dan pasar bebas, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan informatika, demokratisasi, hak asasi manusia dan lingkungan hidup, desentralisasi dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Apalagi, seperti diungkapkan Malik Fadjar, ketika “kosmopolitanisme” dipegangi semacam “ideologi” dan “multikulturalisme” menjadi semacam “visi hidup berperadaban”, dunia pendidikan kita semakin banyak dituntut untuk mampu menyapa perbedaan budaya, sosial dan agama.
Pendidikan, sekali lagi, bukan sekadar mengajarkan atau mentransfer pengetahuan, atau semata mengembangkan aspek intelektual, melainkan juga untuk mengembangkan karakter, moral, nilai-nilai, dan budaya peserta didik. Dengan kata lain, pendidikan adalah membangun bangsa, membangun peradaban, membangun masa depan bangsa. Karena itu, untuk meningkatkan harkat dan martabat sebuah bangsa pada era globalisasi ini, tidak ada jalan lain kecuali meningkatkan kualitas pendidikan.
Salah satu faktor yang menentukan kualitas pendidikan adalah guru. Sebagai komponen utama dalam sistem pendidikan nasional, guru sering dianggap pihak yang paling bertanggung jawab terhadap tinggi-rendahnya mutu pendidikan, meskipun pada dasarnya pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara orang tua, masyarakat dan pihak pemerintah. Di dalam pendidikan persekolahan, kualitas guru memang sangat menentukan mutu kelulusan atau tamatan peserta didik. Terdapat berbagai syarat untuk menjadi guru yang berkualitas, sebagaimana dikemukakan Athiyah Al-Abrasyi, seorang ahli pendidikan Islam. Pertama, guru harus selalu mengetahui karakter murid. Kedua, guru harus selalu berusaha meningkatkan keahliannya, baik dalam bidang yang diajarkannya maupun cara mengajarkannya. Ketiga, guru harus mengamalkan ilmunya dan jangan berbuat berlawnan dengan ilmu yang diajarkannya.
Memang tidak mudah menemukan sosok guru yang mumpuni semacam itu, yang tdak hanya sekadar mentransfer pengetahuan, tetapi sekaligus mampu mengembangkan karakter, moral dan nilai-nilai kepada murid-muridnya. ***