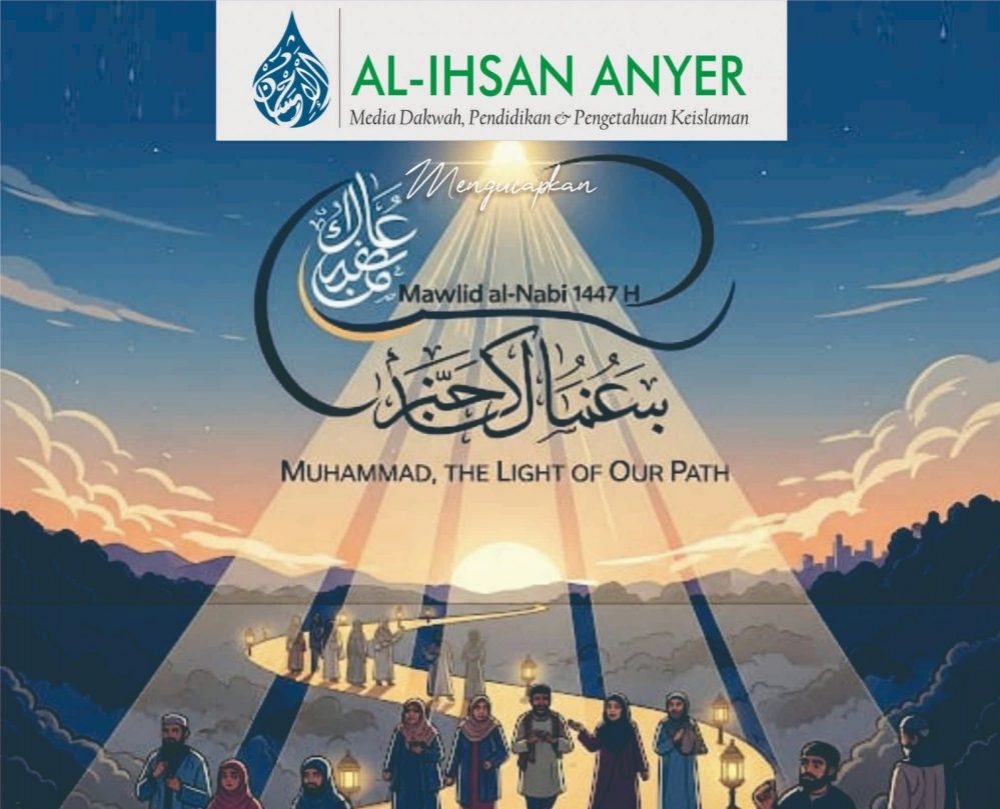H. A. SURYANA SUDRAJAT
Pada dasawarsa 1970-an dunia pendidikan sempat diguncangkan oleh gagasan radikal Ivan Illich lewat bukunya Deschooling Society. Illich mengganggu keyakinan masyarakat, yang diturunkan dari generasi ke genarasi, yang telah berupaya menjadikan dunia sebagai tempat yang lebih baik dengan cara menyediakan lebih banyak persekolahan. Namun, yang didapatkan dari persekolahan hanyalah pelajaran yang memaksa semua anak memanjat tangga pendidikan yang tak berujung, yang hanya menguntungkan individu-individu yang sudah mengawalinya sejak dini, yang lebih sehat atau yang lebih siap. Sisanya hampir pasti gagal.
Menurut Illich, pengajaran yang diwajibkan di sekolah membunuh kehendak banyak orang untuk belajar secara mandiri. Pengetahuan diperlakukan ibarat komoditas, dikemas dan dijajakan, diterima sejenis harta pribadi oleh yang menerimanya, dan selalu langka di pasaran. Menurut dia, keberadaan sekolah memproduksi permintaan akan persekolahan. Di sekolah kita diajar bahwa belajar yang bernilai adalah hasil kehadiran kita di kelas; bahwa nilainya meningkat jika makin banyak masukan yang kita peroleh dan akhirnya bahwa nilai ini bisa diukur dan dicatat lewar gelar-gelar dan ijazah-ijazah. Gagasan Illich tentang pembebasan masyarakat dari persekolahan terus meredup di tengah upaya pemerintah yang gencar mewajibkan anak-anak bersekolah. Dan tingkat pendidikan masyarakat selalu dijadikan komponen penting indeks pembangunan manusia (human development index atau HDI) suatu negara, wilayah atau daerah.
Akan tetapi, seiring perjalanan waktu, dunia pendidikan mengalami guncangan yang mungkin tidak terbayangkan sebelumnya, ketika dunia memasuki era yang disebut revolusi industri 4.0. Revolusi industri generasi keempat ini ditandai dengan kemunculan komputer super, kecerdasan buatan atau intelegensi artifisial. Ini adalah era yang menempatkan teknologi informasi sebagai basis dalam kehidupan manusia. Segala hal menjadi tanpa batas (borderless) sehubungan penggunaan daya komputasi dan data yang tidak terbatas (unlimited). Era revolusi industri 4.0 telah menempatkan perkembangan internet dan teknologi digital yang massif sebagai tulang punggung pergerakan dan konektivitas manusia dan mesin. Hal inilah yang telah dan akan terus mendisrupsi berbagai aktivitas manusia.
Pada era 4.0 ini kita menaksikan perusahaan-perusahaan besar kelas dunia mengalami guncangan bahkan harus gulung tikar. Masa hidup perusahaan semakin pendek, kebanyakan lebih dahulu mati atau digantikan usaha baru. Penggunaan mesin lebih menguntungkan Akibatnya banyak pekerjaan yang hilang, digantikan robot atau kecerdasan buatan. Saat ini pekerjaan yang bersifat rutin dan harian sudah banyak diambil alih mesin. Maka, tenaga kerja manusia pun harus siap berpindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lainnya. Menurut perkiraan Catur Ugiyanto, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, 65 persen manusia sekarang tidak mengetahui kelak memiliki profesi seperti apa. Smentara, 75 juta-375 juta manusia di dunia juga terancam beralih profesi di era revolusi industri 4.0. Hal ini disebabkan karena karakteristik era 4.0, yakni big data, internet of things, cloud computing, dan cognitive computing, yang bermuara pada terciptanya cyber physical system atau yang dikenal sebagai robotisasi yang mulai banyak digunakan di industri. Karena pekerjaan manusia banyak yang mulai digantikan mesin, maka tenaga manusia menjadi komoditas sekunder lantaran penggunaan mesin lebih menguntungkan. Ke depan pekerjaan yang masih belum bisa diambil alih oleh mesin dan robot adalah pekerjaan yang membutuhkan kemampuan dalam melakukan analisa, mengambil keputusan atau berkolaborasi.
Sebagaimana halnya perusahaan, dunia pendidikan pun akan bernasib sama jika tidak segera melakukan perubahan dan menyesuaikan peranannya sesuai tuntutan zaman. Guncangan itu sudah terasa terutama di perguruan tinggi. Bahkan Prof. Clayton Christnsen dari Harvard Business School, penulis buku The Innovative University, memprediksi separo dari 4.000 perguruan tinggi di Amerika Serikat akan bangkrut dalam beberapa dasawarsa mendatang. Dan bukan hal yang mustahil, sekolah-sekolah pun bakal mengalami nasib serupa. Untuk itu diperlukan persiapan sistem pembelajaran yang lebih kreatif-inovatif, seperti penyesuaian kurikulum pembelajaran, dan peningkatan kemampuan peserta didik dalam penguasaan teknologi informasi.
Beberapa kompetensi yang diperlukan peserta didik dalam menghadapi era industrI 4.0 di antaranya kemampuan memecahkan masalah, beradaptasi, kolaborasi, kepemimpinan, dan kreatifitas serta inovasi. Mereka harus dipersiapkan memiliki kemampuan dasar computational thinking, nalar yang kuat, kreatif, kritis, dan inovatif. Mereka juga harus dibiasakan tidak berpikir kecil dan instan, tetapi senang berlatih berpikir out of the box, bahkan berpikir out of the mainstream logic. Jawaban-jawaban ilmiah atas segala keingintahuan harus dibiasakan sejak dini karena generasi masa depan Indonesia harus kmenjadi inventors dan industry disrupters. Diarapkan mereka akan ikut menata ulang kehidupan dengan lebih baik melalui kemampuan dalam hal kecerdasan buatan (AI), bioscience, dan rekayasa energi. Oleh karena itu, mereka harus diberikan kesempatan berlatih untuk menemukenali bakat dan potensinya dalam penguasaan pengetahuan dasar ilmiah, matematika, engineering, ekonomi, dan seni
Tentu pola pendidikan era lama kini menjadi kurang relevan untuk diterapkan pada generasi zaman ‘now’ yang terkena dampak langsung disruptif teknologi. Para pendidik harus berani merefleksikan kembali perannya di depan kelas. Sekarang tidak zaman lagi istilah ‘guru selalu benar’ karena pengetahuan sudah bisa diakses dari banyak sumber. Meski begitu, tidak berarti tugas pendidik di zaman digital ini menjadi tidak penting. Sebab, bagaimanapun, tugas seorang guru bukan hanya mentransfer ilmu dan kereampilan kepada anak didiknya atau menjadikan mereka pintar, tetapi juga memberi motivasi, membangun karakter sehingga menjadi insan atau pribadi yang berintegritas. Atau dalam bahasa Ki Hadjar Dewantara: Di depan memberi panutan, di tengah memberi semangat dan di belakang mampu mendorong. Selain memberikan motivasi, guru juga menjadi filter dari beragam literasi media yang ditemukan anak didik agar tidak mengarah pada hasil yang kontra produktif. Dengan kata lain, zaman boleh berubah, begitu pula tradisi, tetapi esensi atau nilai tetap harus dipertahankan.[]